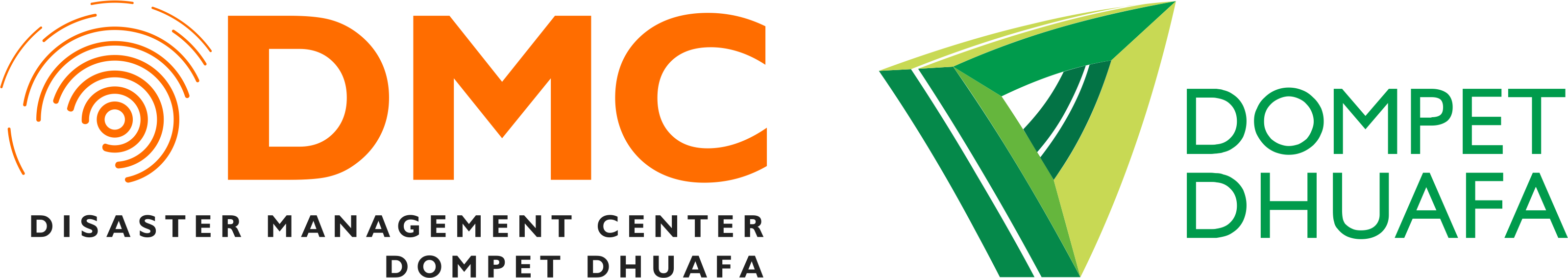Serang, Banten—”Kekayaan masyarakat adat dalam menanggulangi (krisis iklim) ini isu yang relavan,” pungkas Arif Rahmadi Haryono Kepala Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa 2022-2024.
Dengan merebaknya perubahan iklim saat ini, pemerintah dan masyarakat saling mencari inovasi untuk menghadapi bencana di sekitarnya.
Berbagai pihak mencari inovasi dari teknologi terkini hingga meniliki wawasan masa lampau. Teknologi tercanggih hingga kearifan lokal.
Hal ini tercuat dalam diskusi publik Pekan Rakyat Lingkungan Hidup yang digagas oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dengan tema ”Menggugat Krisis dan Bencana Ekologi: Meretas Jalur Pembangunan yang Adil dan Berkelanjutan untuk Keselamatan Rakyat” di Aula Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanudin, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten pada Senin (03/06/2024).

”Di mana saat ini banyaknya masalah mulai dari kemiskinan ekstrim, potensi kelaparan yang tinggi, dan lainnya, tetapi kemudian masyarakat adat itu punya satu cara intelektual yang sudah menjadi turun-temurun,” lanjut Arif.
Kearifan lokal (local wisdom) merupakan bagian dari sistem budaya, biasanya berupa larangan-larangan yang mengatur hubungan sosial maupun hubungan manusia dengan alamnya.
Kearifan lokal berfungsi untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan aset yang dimiliki suatu masyarakat sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya dari generasi ke generasi selanjutnya tanpa merusak atau menghabiskan aset tersebut.

Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, menginisiasikan gerakan penghijauan yang bertujuan untuk menyembuhkan kondisi bumi yang tiap tahun semakin bertambah rusak serta memperbaiki kondisi iklim yang semakin tidak menentu akibat aktivitas manusia yang mencemari lingkungan.
Hal sesederhana seperti cerita rakyat turun-temurun pun merupakan kearifan lokal yang relevan bagi penanggulangan bencana.
Sebut saja tradisi lisan Smong dari Pulau Simeulue, Aceh. Cerita Smong disampaikan kepada generasi muda termasuk anak-anak dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh.

Tradisi ini membuat masyarakat lebih siap siaga hadapi bencana tsunami, hal ini diklaim mampu menekan tingkat korban akibat bencana tsunami Aceh 2004 lalu.
Kemudian di Pariaman, Sumatera Barat ada ”hoyak tabuik” (prosesi mengguncaang patung Tabot), sebuah tradisi penanaman cemara dan mangrove di pesisir pantai untuk mengantisipasi ancaman abrasi dan tsunami di sekitar laut Kota Pariaman.
Sedangkan di suku Baduy, Banten, ada tradisi bernama pikukuh karuhun, sebuah aturan adat untuk melarang membangun rumah dengan mengubah jalan air, mengubah kontur tanah, dan meratakan tanah untuk pemukiman.
Ketiga kearifan lokal di atas hanya segelintir contoh saja, masih banyak contoh-contoh lainnya. Hal seperti ini yang luput dari masyarakat wilayah perkotaan yang melabeli diri mereka sebagai bagian peradaban modern.

”Saya khawatir kita sebagai masyarakat modern melabeli diri sebagai paling paham, paling berperadaban dalam mengelola bumi dibanding komunitas masyarakat adat. Padahal kearifan lokal dari masyarakat adat itu jauh lebih paham bagaimana caranya beradaptasi dengan bumi dan lingkungan,” tambahnya.
”Masyarakat modern tidak tahu bagaimana adaptasi dengan alam, saya sepakat bahwa tidak ada bencana alam, yang ada adalah kita tidak mau mencari tahu pengelolaan sumber daya alam (dengan baik tanpa harus eksploitasi berlebihan dan membahayakan manusia) sehingga kita tidak mampu beradaptasi dengan sekeliling”.
Selain karena minimnya semangat mempelajari kearifan lokal, ada kecenderungan untuk mengabaikan masalah atau konflik yang terjadi di masyarakat saat terjadi bencana. Baik bencana alam, non-alam, bahkan sosial.

Hal ini seringkali terjadi lantaran masyarakat terposisikan sebagai objek bukan sebagai pelaku utama, garda terdepan, atau pihak pertama dalam menghadapi dan meminimalisir dampak bencana di sekitarnya. Hasilnya masyarakat merasakan dampak yang besar akibat bencana di sekitarnya.
”Seringkali kita menempatkan masyarakat umum atau masyarakat adat itu dalam posisi sebagai objek maka ketika terjadi sesuatu terkait dengan, misalnya pembangunan, itu seringkali memunculkan konflik horizontal. Entitas yang semestinya menjadi pihak penengah atau pendamai, justru abai terhadap konflik tersebut. Ketika konflik pecah yang kelimpungan justru masyarakat itu sendiri,” pungkas Arif.
Atas dasar itu penting sekiranya jika seluruh pihak mencoba eksplorasi kekayaan intelektual maupun budaya dan lainnya untuk mencari solusi dalam penanggulangan bencana di sekitarnya. Penting juga dikiranya mengubah perspektif penanggulangan bencana dengan menempatkan masyarakat sebagai agen/ aktor utama dalam penanggulangan bencana ketimbang hanya sekedar menjadi penerima manfaat atau korban bencana itu sendiri. (AFP/ DMC Dompet Dhuafa)