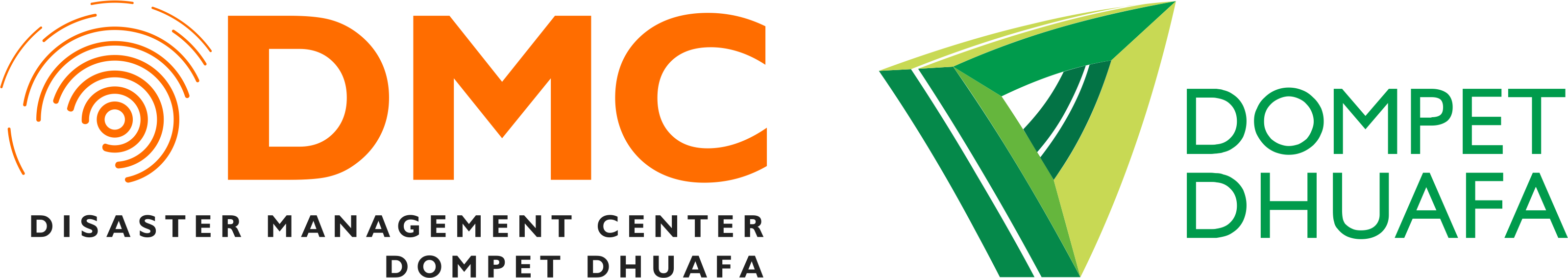Dalam konteks negara Indonesia, selain jenis musik yang disebutkan di atas, terdapat satu jenis musik yang jadi ciri khas Indonesia yakni musik dangdut. Dalam buku yang ditulis Andrew N. Weintraub, yang berjudul Dangdut Stories :A Social and Musical History of Indonesia’s Most Popular Music (2010).
Menurut Andrew keterkaitan antara dangdut dan masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tiga konsep: (1) dangdut merupakan bagian dari rakyat; (2) dangdut diperuntukan untuk rakyat; (3) dangdut adalah rakyat itu sendiri (Weintraub, 2010: 82).
Kemunculan dangdut sendiri merupakan cerminan alami rakyat, berbeda dengan music pop, rock, jazz, atau bentuk lainnya yang ada di Indonesia, yang sebagian besar unsur musiknya didatangkan dari Eropa atau Amerika Serikat. Bentuk awal dangdut didasarkan pada instrumen, timbre, dan memiliki besar keterpengaruhnya dari berbagai genre impor, seperti budaya Melayu dan India.
Pada tahun 1979, kritikus budaya dan penyair Emha Ainun Nadjib (Emha) mengkritik orang Indonesia karena kehilangan “jiwa dangdut” mereka. Hal ini terjadi saat produk-produk dari Barat mulai membanjiri pasar Indonesia, yang mengakibatkan penurunan masyarakat yang suka dengan musik dangdut. Modernitas atau segala sesuatu yang dianggap modern mungkin terlihat bagus di luar, tetapi ia menyamarkan masalah sehari-hari yang dihadapi sebagian besar orang Indonesia, dan mengancam akan memperburuk kesenjangan sosial (Weintraub, 2010: 84).
Dangdut berkembang di lingkungan perkotaan yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial pada akhir 1960-an dan awal 1970-an dalam wilayah yang termasuk Bangunrejo (Surabaya), Sunan Kuning (Semarang) dan Planet Senen (Jakarta). Hal ini meminggirkan jenis musik lainnya seperti pop dan rock di Indonesia. Musik populer indonesia (pop indonesia) dan rock tidak ada akar sejarah yang menghubungkan mereka dengan penderitaan rakyat. Dengan model pop Amerika, gaya vokal yang manis, tempo lambat, dan kurangnya humor dalam pop Indonesia tidak sesuai dengan keinginan dan aspirasi kaum urban kelas bawah (Weintraub, 2010: 84).
Menurut Ariel Heryanto (dalam Weintraub, 2010: 85) dangdut memukau para tukang becak dan bajaj, penjaja sop dan rokok, pedagang pasar dan pedagang yang tinggal di jalanan, gang, dan kawasan kumuh Jakarta dan perkotaan lainnya. Pekerja industri perkotaan—mereka yang bekerja di lingkungan kerja yang paling berbahaya, kotor, dan sulit—tidak hidup dalam alunan musik pop Indonesia yang lembut dan mewah. Suara mentah yang digerakkan oleh perkusi dangdut jauh lebih akrab di telinga para pekerja industri di perkotaan.
Tidak jarang para musisi pop akhirnya turut serta menghasilkan produk musik dangdut untuk ikut dalam tren musik dangdut pada tahun 1960an dan 1970an. Sebagian besar karena keberhasilan rekaman Ellya Khadam, suara orkes Melayu India menjadi kekuatan yang signifikan dalam industri music dan juga Rhoma Irama (Weintraub, 2010: 86).
Musik juga digunakan untuk mengidentifikasi suatu kelas sosial. Pada awal 1970-an, dangdut sering ditampilkan di majalah Aktuil dan media cetak populer lainnya pada masa itu sebagai musik yang terbelakang dan kampungan. Musik pop dan rock dicirikan dengan dunia modern atau musik gedongan. Dangdut adalah musik jalanan, musik yang kerap kali diputar di warung makan pinggir jalan, lingkungan, dan ruang terbuka. Sedangkan rock and pop (dimainkan di gedung-gedung: klub malam, hotel, dan bar) (Ramedhan 1977; dalam Weintraub, 2010: 106-107). Perbedaan ini tercermin dalam istilah sosial ekonomi kampungan dan gedongan. Kelompok gedongan, termasuk anggota band rock yang sangat sukses Panbers dan God Bless, terdiri dari anak muda kelas menengah dan atas. Mereka mampu membeli alat musik dan rekaman terbaru dari Amerika Serikat dan Inggris (Weintraub, 2010: 106-107)