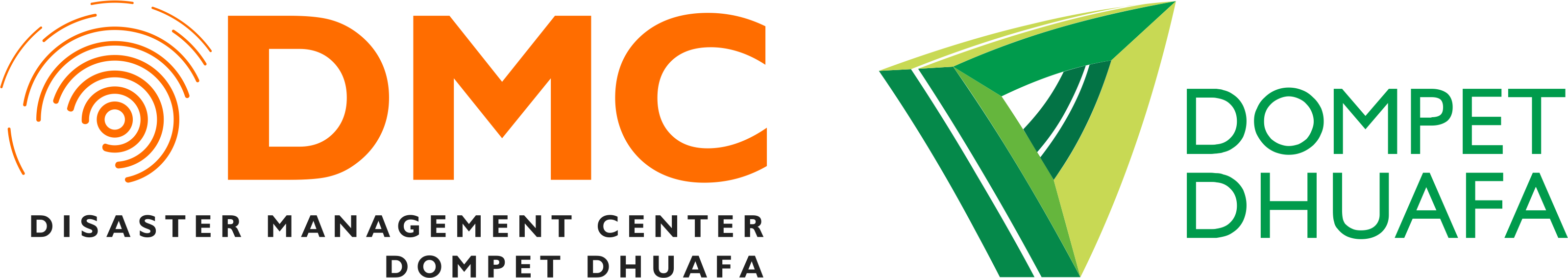oleh Juli Prasetya (seorang penulis muda asal Banyumas. Ia menulis puisi, cerpen, dan esai. Sekarang sedang berproses di Bengkel Idiotlogis asuhan Cepung)
Petani sebagai satu laku budaya dan sebagai laku hidup untuk mempertahankan keberlangsungan umat manusia di sepanjang peradaban zaman. Usianya boleh jadi lebih muda dari usia profesi pemburu di zaman batu, atau orang-orang yang hidup dengan cara nomaden. Namun peradaban petani, boleh jadi merupakan peradaban yang megikuti gerak zaman manusia di seluruh dunia. Dalam peradaban manusia, petani menempati posisi vital dalam menjalankan roda dan gerak zaman tiap-tiap massanya. Petani menjadi satu entitas yang selalu hidup dari masa-ke masa, tiap daerah, tiap wilayah, tiap negara, dan tiap-tiap peradaban. Sudah bisa dipastikan bahwa seluruh urat kehidupan di seluruh dunia pasti memiliki peradaban petani dan pertanian dalam DNA peradabannya.
Dalam mitologi Jawa sendiri, ada dewa dan dewi yang mewakili tiap-tiap entitas dari kehidupan dan alam tempat mereka tinggal dan hidup berdampingan, entah itu antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan alam yang tak kasat mata. Dalam kehidupan petani misalnya, khusunya petani Jawa tentu saja mereka tidak bisa lepas dari satu keyakinan tentang entitas dewi padi, sebagai ibu dari segala pengejawantahan tentang kesuburan dan anugerah melimpah. Dewi Sri yang melambangkan satu kesuburan yang abadi, yang dijadikan sebagai perlambang sebuah anugerah bagi dunia petani. Dewi Sri menjadi analogi tentang harapan, bagaimana petani yang menggarap lahannya tidak merasa sendiri, akan ada masa-masa di mana mereka akan melakukan panen yang penuh berkah dan indah yang akan menanti mereka di depan sana.
Maka tepat di titik ini, alam, petani, dan tradisinya kemudian dibentuk dari hal-hal atau dari entitas-entitas yang demikian. Petani harus menyatu ke dalam alam, atau petani hari ini memang harus kembali ke dalam alam. Karena alam adalah saudara tua dari peradaban umat manusia itu sendiri. Namun dalam sejarah perkembangannya, peradaban modern dengan industrialisasi dan berbagai macam penemuan teknologi yang mengadopsi sistem kapitalis seperti sekarang kemudian mengakibatkan petani dan alamnya tergerus perlahan, mereka seperti ingin dipisahkan atau diputuskan hubungannya dengan alam. Petani seakan terputus hubungannya dengan alam hidupnya, maupun alam pikirannya. Pembangunan infratsruktur yang terkadang tidak memiliki program lanjutan, malah kemudian mengakibatkan petani tak jarang kehilangan lahan garapannya, sehingga ia kemudian secara paksa dipisahkan dengan alamnya, dipisahkan dari alam tempat ia menanam biji-biji harapannya, biji-biji kehidupannya.
Maka untuk mengatasi hal itu kemudian para petani memiliki tradisi untuk mempertahankan kehidupannya, entah kehidupannya secara mikrokosmos, maupun makrokosmos, alam pikiran dan alam hidup petani. Mereka ingin mengembalikan dan mempertahankan sekaligus menjaga itu melalui laku tradisi.
Tradisi petani ini kemudian melahirkan berbagai macam seni dan budaya yang digunakan sebagai pengingat dan penjaga alam pikiran dan alam hidup petani. Seperti bagaimana merayakan masa panen, bagaimana memilih bibit, bagaimana cara menghitung masa tanam, bagaimana pengairan yang baik, bagaimana sistem-sistem organik ini kemudian muncul dalam tradisi bertani, sebagai satu jalan hidup menjadi seorang petani organik yang bisa berjalan meskipun tanpa canggihnya teknologi. Meskipun memang dalam kenyataannya di era kiwari, memang banyak para petani yang kemudian menggunakan teknologi untuk mengembangkan dan melipatkgandakan hasil pertaniannya, tapi toh masih banyak pula para petani yang tetap menjaga hidupnya dengan tetap hidup bersanding dengan alamnya, dengan alam hidup maupun alam pikiran petani itu sendiri. Jadi posisi petani di sini bukan sebagai tukang eksploitasi, tapi ia sebagai partner dari alam tempat di mana Ia hidup dan tinggal. Dan menjaga keseimbangan dengan alam itu menjadi satu tujuan dan visi hidupnya.
Seni-seni yang berhubungan dengan pertanian pun menjadi satu seni tersendiri dalam kehidupan sosial para petani, yang bisa juga dibilang sebagai seni rakyat. Misal kita bisa melihat kelindan itu dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari yang memasukkan unsur-usnru seni rakyat seperti calung, dan ronggeng. Sebagai pengejawantahan dari seni dan hiburan rakyat, seninya para petani.
Di Banyumas sendiri seni tradisionalnya tidak jauh dari kehidupan petani, seperti rengkong, bongkel, calung, gondolio/gandalia. Itu adalah alat-alat musik tradisional yang terbuat dari bambu yang dibuat untuk menemani kehidupan para petani menjaga lahan sawahnya, menunggu ladangnya agar tidak diserang hama dan hewan buas. Lalu kemudian ada cowongan, kothekan, ujungan, baritan, tradisi ini tidak lepas dari kultur petani. Seperti cowongan misalnya, yang dilaksanakan ketika kemarau panjang melanda di sebuah desa atau wilayah pertanian, dan cowongan itu dilakukan untuk memanggil hujan. Hujan sebagai satu entitas penting dalam dunia pertanian. Tanpa air bagaimana tanaman akan hidup, tanpa air bagaimana peradaban petani akan hidup. Maka cowongan mengakomodasi itu, cowongan tahu memang sepenting itulah peran air dan hujan dalam kehidupan petani di seluruh dunia.
Lalu sejarah kemudian mencatat, bagaimana ekploitasi besar-besaran kepada tanah dan para petani di Banyumas mulai digenjot habis-habisan ketika Perang Dipangara berakhir. Maka untuk menebus biaya Perang Jawa itu, wilayah Banyumas dijadikan sebagai wilayah gadaian yang awalnya di bawah kekuasaan Surakarta, kemudian berpindah tangan ke penjajah.
Di sinilah sejarah penderitaan petani Banyumas yang dipaksa melakukan Tanam Paksa itu dimulai. Pajak terbesar yang dipungut oleh Pemerintah kolonial untuk mengganti rugi biaya perang, dibebankan kepada para petani. Selain petani orang-orang yang terjajah itu juga dipaksa untuk melakukan kerja rodi (zaman penjajahan Belanda) dan romusha (era penjajahan Jepang). Maka di titik inilah memang tidak semua sejarah tentang petani itu adalah sejarah yang indah-indah yang penuh dengan keindahan bentangan alam dan panen yang melimpah ruah, tapi di sana juga ada kelindan sejarah yang berdarah, sejarah perjuangan para petani untuk bisa hidup dan meneruskan hidup, sampai kemudian merebut kemerdekaan dirinya, merebut kemerdekaan negerinya.
Kelindan alam, petani, dan tradisi ini tidak bisa dipisahkan begitu saja, mereka memiliki semacam koneksi atau hubungan yang sangat erat, kuat, dan mengikat, maka jangan coba-coba untuk memutuskan hubungan itu. Sehingga para petani di era kiwari sudah sepantasnya mengerti dan tahu asal-usul dan jati dirinya sebagai seorang petani yang tidak lupa dengan alam hidup, dan alam pikirannya. Dengan tradisi-tradisi dan kesenian yang dibuat oleh para leluhur itu menjadi jalan masuk bagaimana tradisi petani itu dilakukan dan terus menerus dijaga keberadaannya di sepanjang perjalanan peradaban besar petani dan hidup manusia. Tradisi-tradisi itu memberikan satu nilai bahwa alam hidup petani itu bukannya hanya perihal-perihal materi semata, tapi di situ juga mengandung satu perjuangan kehidupan dan peradaban manusia dari masa ke masa, dan bagaimana ia menyimpan ingatan dan pengetahuan kolektif itu dalam sebuah seni dan tradisi.
Tapi lagi-lagi memang peran pemegang kebijakan di sini juga sangat penting bagaimana untuk mempertahankan petani-petani di Indonesia umumnya. Bagaimana seharusnya kebijakan yang diambil oleh pemangku itu dibuat harus demi dan untuk keberlangsungan hidup dan kebermanfaatan para petani. Sehingga mereka para petani bisa hidup makmur dan layak dengan profesinya dan hidupnya. Sehingga di masa depan kita tidak takut lagi dengan fragmen-fragmen tentang “negeri ini kehilangan petani” atau “tak ada masa depan bagi para petani” atau “anak muda enggan menjadi petani, mereka lebih memilih menjadi Tiktokers” misalnya. Coba bayangkan jika sebuah negara tidak memiliki petani? Para petani itulah founder sekaligus aktor di barisan paling depan dari program bagaimana menjaga ketahanan pangan yang sebenar-benarnya di sebuah negara. Mereka itulah ujung tombak dalam artian metaforis sekaligus makna sebenarnya sebagai garda terdepan penjaga ketahanan pangan nasional yang sebenarnya.