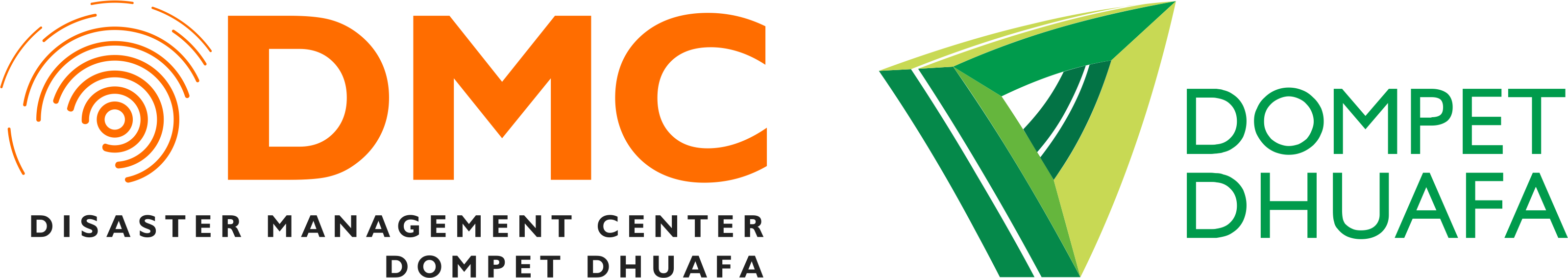Oleh: Christiaan
Pada suatu petang di sebuah kedai kopi, saya—karena kurang kerjaan, kembali menimbang-nimbang pemaknaan saya terhadap hujan, dan kenangan yang saya lekatkan kepadanya. Ya, petang itu sedang turun hujan. Tidak deras-deras dan lama-lama amat. Tapi angin yang datang bersamanya cukup menyiksa banner promo di depan kedai kopi itu, sebelum akhirnya ia tumbang.
Saya pikir, kelewat sering saya selama ini memaknai hujan dan kenangan secara paradoksal. Di satu sisi, sama seperti Scott Stapp vokalisnya band Creed, saya merasa (dan mengharapkan) hujan akan menghapus masa lalu saya, kenangan saya.
Let it rain down and wash everything away.
Harapan dalam lantunan lagu Creed itu muncul, tentu karena ada kenangan yang kurang mengenakkan. Sehingga tak perlulah ia diingat-ingat sebagai voluntery memory. Biarlah ia tersapu bersih oleh hujan agar tak lagi muncul sebagai unvoluntery memory.
Fall down, wash away my yesterdays.
Di sisi lain, saya masih saja senang meromantisasi hujan dengan kenangan-kenangan yang saya miliki. Jangankan hujan, baru mendung sedikit saja saya sudah mereka-reka kenangan manis mana yang bakal saya munculkan, dan menerka-nerka kenangan pahit mana yang nanti bakal menyeruak dari balik awan di kepala saya.
Jadi, ya di sinilah paradoksnya saya kira. Saya mengharapkan hujan turun buat menghapus kenangan. Sementara hujan datang tak pernah tanpa membawa kenangan-kenangan saya, baik yang manis-manis, maupun yang pahit-pahit dan getirnya. Sampai-sampai saya pernah tulis puisi begini:
DUH
Duh, hidup makin aneh-aneh saja
sejak dia pamit entah ke mana
Siang ini
di kedai kopi sepi pelanggan
Saya memesan secangkir kopi krim panas
tapi yang datang malah hujan
dan kenangan diantarkan setelahnya
Iuh, puisi yang menggelikan bukan?
Setelah hujan petang itu reda, dan banner promo ditegakkan kembali oleh si barista, saya ambil kesimpulan. Atau lebih tepatnya, perubahan sikap pada hujan dan kenangan. Saya putuskan berhenti mengharapkan hujan menghapus kenangan saya. Dan saya janji tak akan lagi meromantisasi hujan.
Kenangan bakal menguap. Tapi hujan akan selalu turun membawa pulang kenangan itu. Mengembalikannya kepada si empunya kenangan. Hujan akan selalu datang bersama kenangan. Seperti kenangan yang selalu datang bersusul hujan. Entah di pipi, atau di hati.
Lagipula
Lagipula, ada hal lain yang lebih mengkhawatirkan. Literally mengkhawatirkan. Bukan yang kita buat-buat mengkhawatirkan dengan cara mengindividualisasi masalah-masalah kenangan seperti saya ceritakan sebelumnya. Hal yang lebih mengkhawatirkan itu adalah, ya benar, krisis iklim.
Tidak hanya akrab dengan kenangan, hujan juga akrab dengan longsor dan banjir bandang. Saat kita memandang nanar hujan dari balik kaca kafe sembari memikirkan kenangan, di lain tempat ada orang-orang yang tertimbun longsor karena tak sempat mengungsi sebab telat mendapat peringatan dini bencana. Saat kita mengharapkan kenangan tersapu hujan, di lain tempat orang-orang tengah mendaraskan doa-doa dari tenda pengungsian, agar rumah mereka tidak tersapu banjir.
Bencana, bencana, ya demikian kita menyebutnya. Curah hujan terlalu tinggi, cuma itu-itu saja pernyataan template yang kita dapatkan dari para pemangku kewajiban. Tapi benarkah hujan adalah satu-satunya yang pantas didakwa? Para pengungsi bertanya-tanya. Lalu beroleh jawabankah mereka? Atau cuma dikasihani dengan paket-paket bantuan yang sudah kena potong atas. Huahaha. Lucu? Tidak. Tapi ya tertawa saja. Air mata sudah habis menangisi nasib.
Belakangan, di sekitar kampung saya di Tapanuli, terjadi longsor yang menghancurkan permukiman dan merenggut nyawa. Wilayah itu memang rawan bencana. Tapi ajaibnya, tak jauh dari situ, ada pula konsesi perusahaan ekstraktif. Perusahaan ini membabat hutan, lalu menanami sejenis pohon untuk keperluan produksi mereka. Jadilah hutan monokultur. Ekosistem terganggu.
Hujan turun. Kata penduduk, hujan itu biasa saja. Artinya, dari dulu hujannya memang begitu-begitu saja. Tapi sekarang, kenapa sekonyong-konyong bisa longsor? Harusnya fakta terganggunya ekosistem hutan sudah mengantar kita pada dua pertiga jawaban. Sepertiganya lagi, layaknya sih kita serahkan pada si korporasi dan pemerintah untuk menjawabnya. Kenapa kegiatan industri ekstraktif itu tak layak dituduh sebagai biang longsor?
Tentu saja yang sepertiga itu juga tidak dijawab dengan serius. Malah kita wargalah yang dibebani untuk memberi bukti, jikalau longsor itu memang disebabkan oleh kegiatan industri ekstraktif di sekitar wilayah rawan bencana. Sudah tentu kita mengalah. Kita beri bukti berdasar pengetahuan dan pengalaman luhur kita. Tapi kemudian tidak berdampak apa-apa, karena dianggap tidak saintifik dan malah teriakan protes kita seringkali dituduh telah didikte oleh kepentingan kelompok-kelompok tak bertanggung jawab yang hanya ingin memecah belah bangsa.
Ah, saya ini mau bicara apa sebenarnya. Dari hujan, kenangan, sekarang ke krisis iklim. Ya saya cuma mau bilang. Kalau kita sudah berhasil menyiasati kenangan yang datang bersama hujan, harusnya kita juga bisa menyiasati krisis iklim. Bisa kita—terutama pemerintah nih, mulai dengan berhenti menyalahkan hujan atas banjir dan longsor, seperti kita berhenti menyalahkan hujan atas tertikamnya luka yang sudah mengering oleh kenangan.
Lalu kita bisa lanjutkan dengan meningkatkan kepekaan pada kelestarian lingkungan dan mengawal kebijakan pembangunan. Ada harapan. Tapi seberapa kuat kita menggenggam harapan itu. Dan seberapa ngotot kita membuatnya jadi kenyataan? Semua bermula dari diri masing-masing. Tapi permulaan yang sistemik dan berpihak dari pemerintah bakal punya dampak lebih besar. Tanpa kebijakan yang berpihak dari pemerintah, pada akhirnya, kita cuma bisa menempuh jalan sunyi: menepi ke pinggiran kota, menjalani hidup dengan jejak karbon seminimal mungkin, menyesali kebijakan pemerintah yang tidak bajik, atau, ya.. berceloteh lewat tulisan seperti saya lakukan ini.
Sumber gambar: A Row of Metal Chairs Sitting Next to Each Other by Tatiana Tochilova