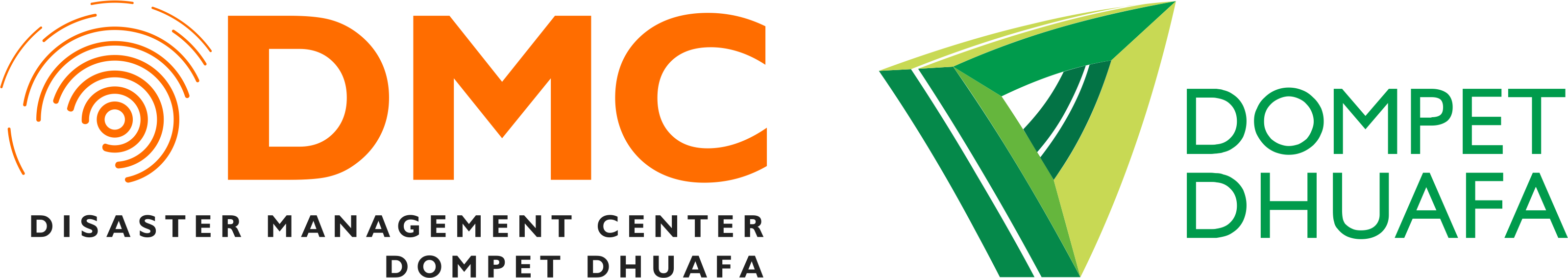Oleh: Juli Prasetya
Aku menulis catatan ini di pinggir jalan, tepatnya di emper toko musik di dekat pertigaan pasar di kotaku. Dengan satu asumsi bahwa seremeh apapun peristiwa bukankah ia berhak untuk dituliskan? Ya kalau itu memang dirasa perlu. Toh apa pula yang akan kita lakukan jika terjebak di cuaca hujan seperti ini, di Juli yang basah. Dan aku seperti tokoh-tokoh dalam cerita Orwell tentang gelandangan yang bertahan hidup dari rumah singgah ke rumah singgah yang lain.
Hujan seperti menceritakan sebuah kisah pada 40 tahun yang lalu. Ia turun tepat pada usianya yang ke 40. Sebagaimana dulu saat ia menguap lalu membentuk awan hujan dan mengendapkan dirinya sendiri selama 40 tahun, baru kemudian ia turun dengan derasnya setelah 40 tahun terlewati. Maksudku hujan yang kita saksikan dan rasakan sekarang sebenarnya ia adalah hujan yang telah bersiap dari 40 tahun yang lalu.
Aku pernah menulis kisah tentang hujan kreatif, yakni hujan yang dapat membuat seseorang yang terkena tetesannya akan menjadi orang-orang kreatif di setiap bidang yang mereka geluti. Entah itu intelektual, penyair, novelis, penyanyi, pelukis, atau seniman dalam dimensi yang paling optimum. Hujan kreatif itu hanya terjadi dalam rentang waktu 1000 tahun sekali. Dan ada seorang miliuner yang mengumpulkan karya-karya dari orang-orang yang terkena hujan kreatif itu.
Aku selalu bertanya, mengapa ketika hujan langit begitu pucat? Atau mengapa ia berwarna putih atau kelabu. Aku tak tahu apakah langit ditutupi oleh awan hujan seperti awan Cumolonimbus misalnya dan ia menutupi sebagian besar langit yang sedang turun hujan. Atau warna pucat itu sebenarnya adalah percikan air yang turun dari awan mendung yang berderai, seperti air terjun dengan pucuk alirannya memiliki banyak lubang, sehingga pancaran itu menyebar dengan luasnya dan muncrat dengan lebatnya. Coba kau bayangkan plastik kresek putih kuat yang memiliki banyak lubang di bawahnya, lalu kantung kresek itu diisi dengan penuh dengan air. Nah begitulah aku menggambarkan percikan ar yang turun dari awan mendung yang berderai itu.
Hujan selalu mengingatkanku pada ingatan dan kenangan. Entah karena rintik suaranya yang menyentuh genting dan seng seperti nyanyian, atau karena memang benar kata orang-orang yang sedang patah hati, bahwa kandungan air hujan itu sebenarnya 1% air dan 99% kenangan (haha). Entahlah, aku sendiri tidak tahu pasti. Tapi yang kutahu adalah ketika hujan turun entah mengapa sisi kreatifku tiba-tiba saja juga ikut menderas. Ya memang bagi sebagian orang hujan dimaknai lebih cenderung dekat dengan kesedihan.
Banyak puisi-puisi sedih atau puisi-puisi cinta berkaitan dengan hujan, tapi aku curiga bahwa orang-orang yang seringkali membawa-bawa hujan dalam puisinya misalnya, mereka pasti akan menepikan kendaraannya ketika hujan turun, lalu memakai jas hujan untuk melindunginya dari guyuran hujan. Ngakunya penyair hujan, tapi ketika hujan turun kok malah melipir ke emper toko untuk melindungi diri, atau memakai jas hujan. Takut sakit katanya.
Ini menurutku juga semacam ironi, mengapa demikian? Karena ketika kita seenak jidat memaknai hujan dan mengeksploitasinya juga dengan membabi buta, tapi di satu sisi kita sendiri ternyata takut dan agak membenci datangnya hujan. Jemuran belum keringlah, membuat sakit dan meriyanglah, mengacaukan jadwal pertemuanlah dan masih banyak lagi lah-lah yang lainnya.
Seharusnya bukankah kita mesti belajar dari jiwa anak-anak yang masih bersih, putih, dan penuh dengan sukacita itu, yang selalu bahagia dan gembira ketika hujan turun. Kebahagiaan dan kegembiraan yang dirasakan oleh jiwa-jiwa anak kecil itu ternyata tidak dirasakan dan dialami lagi oleh jiwa-jiwa yang sudah mulai beranjak dewasa. Ya, diakui atau tidak perlahan kita juga memang kehilangan anak kecil di dalam diri kita sendiri.
Lalu apa yang terjadi, ketika kita tidak memiliki kegembiraan layaknya anak kecil saat mengalami hujan? Ya kita akan menjadi orang dewasa yang selalu menggerutu jika datang sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya seperti hujan yang datang di saat yang tidak kita inginkan misalnya, kita akan terus menerus menggerutu dan bahkan memaki hujan itu. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa hujan itu adalah rahmat. Rahmat yang diturunkan oleh Tuhan ke muka bumi.
Coba sesekali kita melihat langit yang memutih, dan hujan yang bersulih rupa menjadi kabut. Lalu jalanan basah, perasaan basah, dan kenangan adalah ingatan yang selalu gelisah. Lalu bagaimana kita juga menafsirkan tentang hujan? Bahwa hujan memang seringkali hanya mengasihi para petani dan orang-orang yang menangis karena patah hati bukan?
Aku belajar sesuatu dari hujan, bahwa tidak selamanya mendung dan hujan yang sering dimaknai dengan kesedihan dan kemurungan hidup itu akan terus menerus terjadi ke dalam hidup yang tengah kita jalani ini. Bukankah setelah hujan turun dengan lebatnya, menderas, dan kemudian mereda, terkadang kita juga akan menemukan pelangi setelahnya. Dan aku belajar bahwa hidup adalah perputaran dari satu kesedihan ke kesedihan yang lain, dan di antara dua kesedihan itu terselip keriaan yang konyol. Maka manusia hidup dengan memanggul dua kesedihan dan satu kebahagiaan, dan keriaan itu seringkali kita nikmati saat kita tak terlalu sadar bahwa itu adalah sebuah kebahagiaan. Soalnya kita terlalu fokus pada dua kesedihan yang sedang kita alami sampai lupa ada satu kebahagiaan dan keriaan di dalamnya. Bukankah dalam dua kesedihan itu pasti selalu terselip satu keriaan yang bisa dibagi dan dinikmati bersama orang-orang yang kita kasihi?
Foto merupakan dokumentasi pribadi penulis