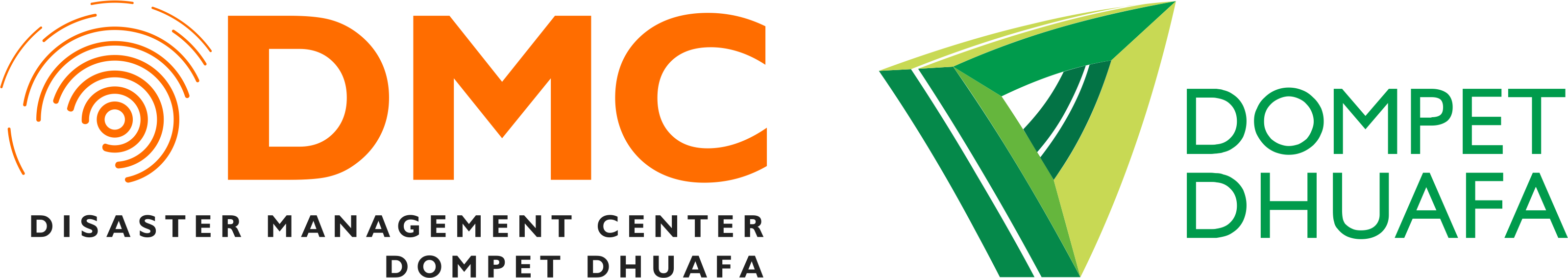oleh: Zahidah Amatillah
Setiap peristiwa yang terjadi pastilah memiliki kebermaknaan hidup. Bahkan tetesan rintik hujan sesedikit itu, memiliki makna yang melekat meskipun tokoh dalam tetesan tersebut telah pergi bertemu penciptanya.
Terlahir di keluarga dengan berlimpah anak menjadikan kami tumbuh dalam banyak cinta. Semua momen kami habiskan bersama. Bahkan sekadar menyaksikan hujan yang turun, kami selalu memosisikan diri duduk berjajar di halaman belakang, dengan ayah yang berada di antara kami. ‘Bagaikan sayap’ itulah arti keberadaan kami bagi ayah.
“Sudah gerimis, sebentar lagi hujan deras!” ayah berteriak dari halaman belakang rumah.
Halaman belakang rumahku cukup luas, 2 x 5 meter. Setengah bagiannya tak tertutup atap, menjadikan hujan bebas masuk. Tempat ini adalah tempat favoritku menghabiskan waktu untuk bemain. Maklum, pagar rumahku yang langsung berbatasan dengan jalan raya menjadikan ibu takut membiarkan anaknya bermain di luar.
“Ayo! Sini!” ayah kembali berteriak sambil melambaikan kedua tangannya.
Teriakan ayah menjadi alarm yang siap berbunyi setiap kali rintik hujan datang. Satu, dua, tiga anak ayah berlari ke sumber suara, diikuti keempat anak lainnya. Kami tak mau melewatkan momen menyaksikan rahmat Tuhan yang turun.
“Nah, kalau sudah rintik begini, tandanya apa?” ucap Kak Lili tersenyum malu sambil mengarahkan jari telunjuk ke arah hidung ayah.
Kak Lili adalah anak pertama, jeda dua tahun, lahir Kak Fafa. Dua tahun berikutnya, lahirlah aku, Zizi. Setelah itu adik Tata, adik Zaza, adik Mumu dan si bungsu, adik Nunu.
“Waktunya jajan pangsiiiittt!” jawab adik Tata berteriak senang.
Kebiasan ayah dan anak-anaknya memang unik saat hujan. Ketika rintik hujan turun, ritual diawali dengan jajan mie ayam pangsit, makan bersama, setelah itu barulah kami mandi hujan bersama.
Saat rintik hujan belum turun bergerombol, kami membagi tugas; ada yang menjaga adik-adik, ada yang jajan mie ayam pangsit di depan gang rumah dan ada yang mengunci pintu garasi agar tidak ada tamu yang datang saat kami mandi hujan.
“Pangsit dataaanggg!” teriak Kak Lili senang sambil menenteng mie ayam pangsit di kedua tangannya. Rambutnya yang hitam telah terlumur oleh tetesan hujan.
Setibanya Kak Lili, kami makan dengan lahap mie ayam pangsit yang masih panas diiringi air hujan yang mulai tampias. Dingin sekali. Namun momen ini sangat hangat bila aku ingat kembali.
“Makan mie ayam pangsit pas lagi hujan kaya gini memang paling enak ya.” ucapku.
Pangsit Gajah Mugkur depan gang rumah kami memang terkenal enak, dengan bentuk mie- nya yang kecil ditambah potongan ayam yang besar serta warnanya seperti semur dengan rasanya yang manis, menjadikan anak kecil tak akan menolak bila disuguhkan.
“Iya enak banget, ya. Semoga sampai kapanpun kita bisa kaya gini terus; makan mie ayam hujan-hujan bareng keluarga.” sahut Kak Fafa.
“Aamiin”, ucap ayah mengaminkan kalimat pendek yang menjadi doa. “Semoga kita bisa selalu minikmati mie ayam Gajah Mungkur saat hujan. Ayah senang melihat anak ayah bahagia. Tetap rukun seperti ini ya, Nak.”
Doa yang diaminkan ayah rupanya tidak lama. Selang beberapa tahun, ayah berpulang menemui penciptanya.
Kini, hujan tak lagi sama. Tak ada lagi tangan yang bergandengan menari membersamai hadirnya. Berdiri di bawah rintiknya pun enggan. Kenangan masa kecil kami hanya bisa diingat kala duduk di halaman belakang dengan rintik hujan yang turun menyeka pipi yang basah.

Tak lagi ku dengar seruan ayah mengajak mandi hujan dengan sangat bahagia. Berlari, menari, bermain bola. Semua adegan yang kami eksekusi dahulu tak bisa diulang dengan perasaan yang sama.
“Tuhan, tak bisakah sedikit lagi kau memberiku waktu menghabiskan hujan bersama ayah?” aku bertanya kepada langit. Namun langit enggan menjawab.
Dulu, seringkali suara kami menerabas udara, berteriak, saling bersahutan dengan suara yang ‘melempem’ dimakan hujan. Ketika langit tak bisa mengeluarkan jawabannya, ayah-lah yang paling setia menjawab setiap ucapan konyol kami semasa kecil.
Aku ingin meneriaki dunia bahwa;
“Mulai hari itu. Langitku tak secerah dulu. Selalu ada rintik dari gelapnya awan yang bernaung. Ada tangis yang mengisak dari sedih yang tertahan. Seikat kenangan yang akan selalu aku genggam dalam ingatan. Bersamamu adalah takdir terindah yang Tuhan berikan. Ditinggal olehmu adalah takdir yang harus aku ikhlaskan”.
Rintik-rintik yang jatuh menjadikanku menjadi orang yang lebih sensitif akan datangnya keberkahan Tuhan. Sedikit lebih emosional, pokoknya, tak ada yang boleh menggangguku melamuni hujan yang turun.
Dalam lamunanku, hatiku terus berbicara, seolah aku sedang berdialog kepada hujan. Dalam riuhnya rintik yang jatuh bergantian, aku tetap sepi.
“Ada rindu berulang yang seharusnya menemukan jalan pulang. Namun, kata pulang menjadi kata yang tak mungkin. Sebab, ia yang telah pergi tak akan pernah kembali. Salah satu bagian terberat dari hidup adalah mencintai seorang hamba dengan memberikan segala rasa yang dimiliki. Namun, harus siap kehilangan. Sebab, yang fana akan kembali kepada Tuhannya, yang tentu lebih mencintainya.”
Secara tidak sadar, aku menjadi pandai menulis. Syukurlah, kepandaian menulis ayah sedikit menurun kepadaku. Aku hanya bisa mengenang ayah dalam ingatan dan tulisan yang abadi.
“Tuhan, aku merindu ayah. Kau ambil satu titipan Mu. Ku lepas ia untuk Mu. Karena Kau adalah sebenar-benar pemilik.”
Kini, kenanganku pergi tersapu hujan.